Edi Slamet Irianto: Tahun 2023 Momentum Transformasi Perpajakan Indonesia
Pajak.com, Jakarta – Guru Besar Hukum Politik Perpajakan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Edi Slamet Irianto menilai, 40 tahun reformasi perpajakan mengalami titik jenuh. Reformasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 1983 itu tidak bisa mempersembahkan rasio pajak sesuai potensi fiskal negara dan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka Edi Slamet Irianto mengatakan, tahun 2023 ini merupakan momentum negara melakukan transformasi perpajakan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
“Transformasi perpajakan dibutuhkan oleh negara dan rakyat, bukan sekadar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tranformasi perpajakan yang meliputi kelembagaan, kebijakan, dan administrasi perpajakan. Ini sebagai respons terhadap reformasi perpajakan yang sudah 40 tahun dilaksanakan, tetapi gagal menghadirkan rasio pajak sesuai dengan potensi fiskal negara dan kebutuhan APBN. Negara harus segera mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa harus berutang,” ungkap Edi, kepada Pajak.com di kediamannya, (8/7).
Sebagai gambaran, rasio pajak Indonesia saat ini masa bertengger di level 10,41 persen terhadap PDB atau paling rendah dibandingkan negara ASEAN dan G20. Di ASEAN, rasio pajak tertinggi dicapai Vietnam sebesar 22,7 persen terhadap PDB, lalu disusul Kamboja 20,2 persen terhadap PDB, Thailand 16,5 persen terhadap PDB, Singapura 12,8 persen terhadap PDB, Malaysia 11,4 persen terhadap PDB. Sementara di negara G20, seperti Amerika Serikat mencatatkan rasio pajak pada level 26,58 persen terhadap PDB; Denmark, Prancis, dan Finlandia mencapai di kisaran 40 persen hingga 47 persen terhadap PDB.
Padahal dari perspektif pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari 5 persen pada tahun 2023 dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Republik Rakyat Tiongkok (RTT) atau diantara negara anggota G20.
Maka, Edi menegaskan, transformasi kelembagaan perpajakan menjadi urgen untuk dilakukan demi memenuhi kebutuhan negara maupun rakyat melalui penataan dan fungsi institusi. Ia menyebutkan, ada tiga model kelembagaan perpajakan yang dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Pertama, model pengelolaan pajak oleh satu direktorat jenderal yang melekat dengan Kemenkeu. Kedua, model pengelolaan pajak oleh lembaga otoritas semi independen. Ketiga, model pengelolaan pajak oleh otoritas pajak independen atau lepas dari Kemenkeu. Edi menyebutnya sebagai badan otoritas penerimaan perpajakan/negara.
“Pengelolaan yang bersifat mandiri dan independen, lebih tepat untuk Indonesia. Hal ini demi memenuhi kebutuhan pengelolaan pajak yang selama ini belum berhasil menjadikan APBN mandiri, sehingga nantinya utang tidak semakin banyak, dan kebutuhan kesejahteraan rakyat terpenuhi,” tegasnya.
Edi membandingkan dengan beberapa lembaga negara lain, yang juga dibentuk atas dasar amanah konstitusi, terutama pada bidang ekonomi di Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah Indonesia membentuk delapan kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).
“Sementara, seperti di atur dalam Pasal 23A UUD 1945 mengenai pemungutan pajak, yang kita tahu kontribusinya 70-80 persen terhadap penerimaan negara, amanah UU itu hanya dikelola oleh pejabat setingkat eselon I, DJP di bawah Kemenkeu,” ujar Edi.
Implikasinya adalah DJP tidak akan bisa merespons tuntutan lingkungan, masyarakat, dan negara di waktu yang sama. Disamping itu, Edi juga menilai, dalam struktur kelembagaan terjadi anomali di tubuh DJP sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam Pasal 16 Perpres Nomor 7 Tahun 2015 ditegaskan bahwa direktorat jenderal terdiri atas sekretariat direktorat jenderal dan paling banyak lima direktorat.
“Kenapa terjadi anomali di DJP? karena hanya DJP saja yang didampingi oleh tiga staf ahli menteri keuangan. Di kementerian lain ada enggak seperti itu. Direktur jenderal di kementerian lain paling banyak memiliki direktur sekitar lima, sementara DJP ada 14 direktur. Kenapa ini dibiarkan? Ini tidak lazim sebagaimana eselon 1 lainnya di luar kementerian keuangan. Otoritas perpajakan di Indonesia tidak bisa dikelola hanya satu dirjen pajak. Contoh, Kementerian Investasi/BKPM memiliki 2 ribu (pegawai), itu dikelola seorang menteri. DJP, pegawai sebanyak 46 ribu, kok unit eselon I? Coba dipikirkan dengan baik. Sampai kapan pun reformasi yang dilakukan Kemenkeu atau DJP kalau caranya seperti sekarang ini, tidak akan berhasil meningkatkan rasio pajak di Indonesia,” ujar Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Periode 2021-2023.
Menurut Edi, reformasi perpajakan yang berjalan selama 40 tahun (1983-2023) sebatas melakukan perbaikan yang sifatnya parsial, bukan fundamental sesuai amanah konstitusi. Ia optimistis, badan otoritas penerimaan perpajakan/negara akan menempatkan institusi ini lebih strategis, sehingga pengawasan dapat lebih mudah dilakukan oleh presiden dan rakyat.
“DJP sebagai institusi semakin besar. Ibarat pakaian, sejak dulu yang dipakai masih itu saja. Pakaian sudah sobek, ditambal kembali. Ibarat dulu anak usia 5 tahun, sekarang usia 15 tahun, pakaian itu tidak bisa pakai kembali. Tidak bisa dipaksakan kita memakai pakaian yang bukan usianya lagi. Harus disesuaikan dengan kebutuhan sekarang, karena anaknya sudah besar. Contoh lain, dalam kendaraan bus, dulu metromini cukup karena penumpangnya cuma 30 orang, ini penumpangnya makin banyak. Kenapa dipaksain? Akibatnya rasio pajaknya rendah karena kapasitas DJP kurang atau tidak mampu menampung yang begitu besar dan luas,” ungkap Edi.
Kendati demikian, ia mengusulkan, badan otoritas penerimaan perpajakan/negara ini harus memiliki sumber pembiayaan dan biaya operasional yang tidak bersumber dari APBN, namun swakelola.
“Di awal memang dari negara, namun setelah terbentuk dan menjalankan tupoksinya, maka pembiayaannya berasal dari persentase penerimaan perpajakan atau negara. Kira-kira sama dengan model yang dilakukan lembaga perpajakan di dunia,” ungkap Edi.
Kelembagaan ini menjadi katalisator transformasi pada kebijakan dan administrasi perpajakan. Apabila ketiganya enggan dilakukan, Edi memproyeksi, Reformasi Perpajakan Jilid III yang diejawantahkan salah satunya melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax belum mampu secara optimal menangkap kebutuhan DJP.
“Proses bisnis DJP kita akui bersama ada perbaikan. Namun, dengan adanya core tax, yang membedakan hanya IT (informasi dan teknologi) saja. Harusnya proses bisnis itu tidak hanya bertumpu pada kepentingan internal saja, namun harus linear dengan kepentingan perpajakan Wajib Pajak. Semakin sederhana, cepat dalam pengambilan keputusan, dan aman dari segi arus informasi. Sebab database rawan intervensi para hacker, itu harus dipikirkan, bagaimana jika suatu saat terjadi distorsi,” ujar Edi.
Dengan demikian, ia berprinsip, bahwa badan otoritas penerimaan perpajakan/negara merupakan kebutuhan negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini akan bermuara pada ketaatan Wajib Pajak dan rasio pajak. Edi menekankan, kolerasi tingkat ketaatan Wajib Pajak dengan kesejahteraan rakyat memiliki hubungan yang erat.
“Ketaatan pajak dapat terwujud apabila masyarakat mendapatkan keistimewaan pelayanan maupun fasilitas secara langsung, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Artinya, rendahnya rasio pajak berkorelasi dengan realisasi pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik. Kita mengetahui, 70-80 persen penerimaan pajak untuk APBN. Tapi, bagaimana anggaran yang dari pajak itu dapat mendukung program pembangunan sarana umum dan fasilitas publik? Pembayar pajak itu punya keistimewaan, pelayanan yang bagus, dan jangan dipungut biaya lagi. Ini dapat menanamkan ketaatan pajak masyarakat,” kata Edi.
Ia mencatat, misalnya, pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas publik hanya 16,5 persen dari total pendapatan PDB. Sedangkan, bila merujuk data Bank Dunia, negara-negara berkembang lainnya rata-rata menghabiskan 32 persen untuk fasilitas publik dari PDB.
“Jadi, lembaga perpajakan di tingkatkan kewenangannya, tidak hanya dikelola eselon I sehingga tidak bisa mengambil respons kebijakan yang cepat dan tepat untuk masyarakat. Kebijakan perpajakan harus mengikuti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat,” pungkas salah satu pendiri klaster riset politic of taxation, welfare and national resilience (PolTax) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini.


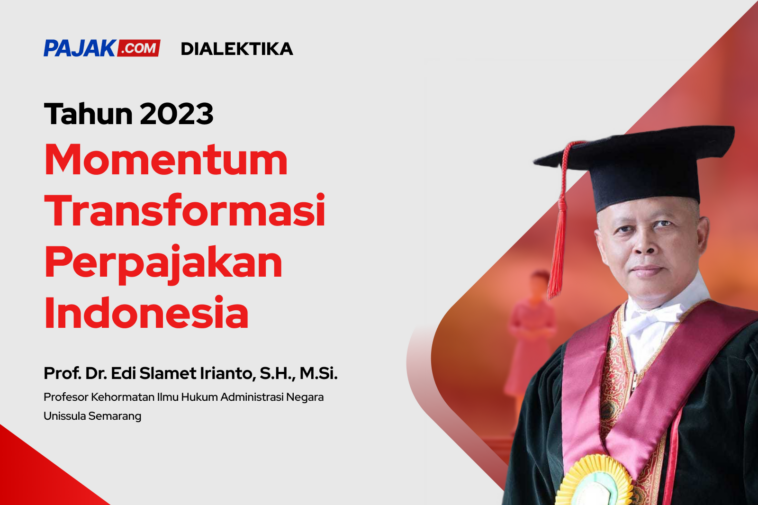
Comments